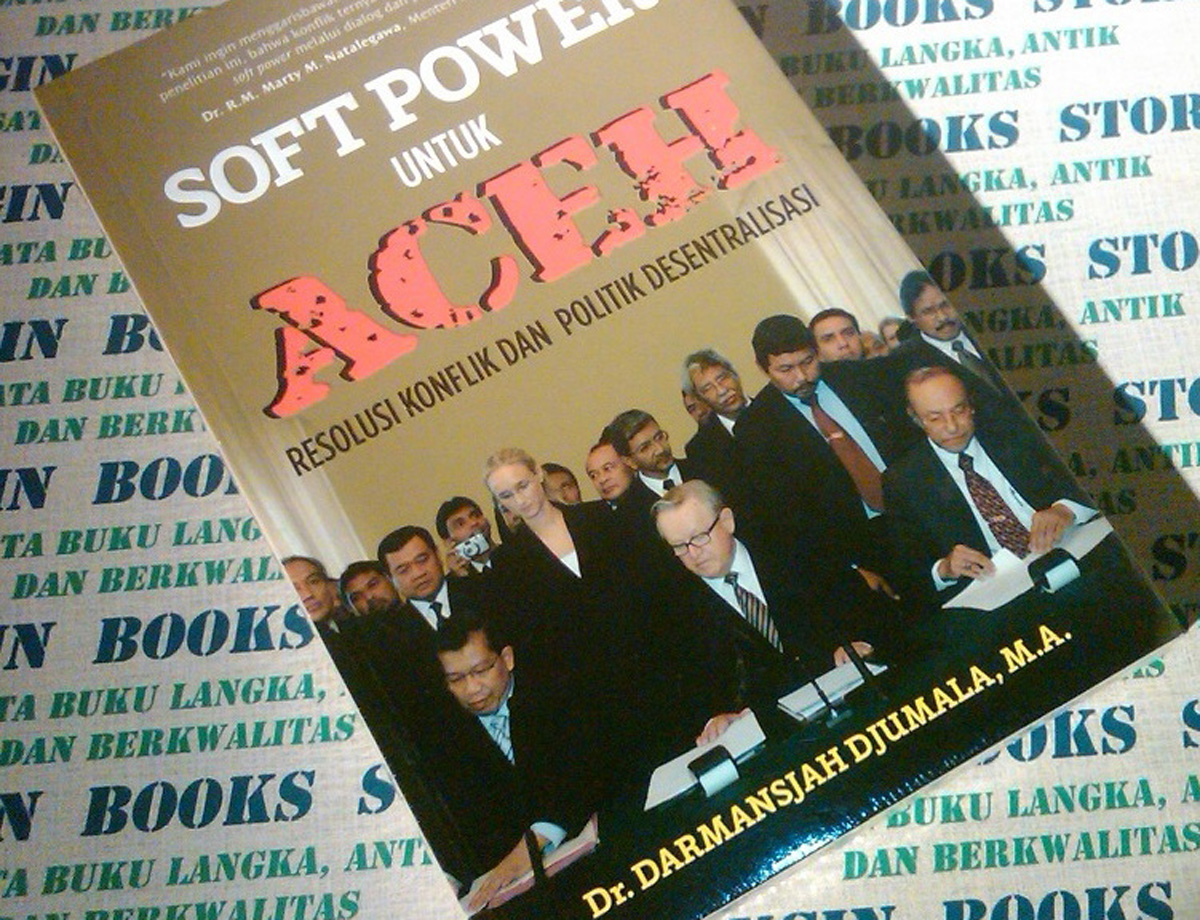Pendahuluan
Konflik Aceh adalah air mata sekaligus mata air. Air mata karena begitu banyak air mata yang tumpah mewarnai dinamika konflik yang terjadi di Aceh. sedangkan disebut mata air dikarenakan konflik Aceh justru menjadi blessing in disguise bagi dunia akademik, dikarenakan begitu banyak “mutiara” yang digali dari konflik tersebut. disamping juga tentu banyak pihak yang memanfaatkannya sebagai “sumur” ekonomi untuk meningkatkan taraf kehidupan pribadi.
Konflik antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam sebuah wilayah Negara merupakan hal yang sering dijumpai. Kita tentu bisa melihat bagaimana sengitnya wilayah catalan dengan Pemerintahan sah Spanyol di Madrid. Tak jarang kontestasi keduanya bahkan masuk ke dalam stadion sepakbola ketika pertandingan La Liga yang mempertemukan antara Barcelona (catalan) dengan tim ibu kota Spanyol, Real Madrid, yang merepresentasikan pemerintahan yang sedang berkuasa.
Beberapa hasil temuan tentang Aceh yang patut diapresiasi bagi perkembangan dunia akademik salah satunya adalah buku karya Darmansyah Djumala ini. Sejatinya buku ini merupakan disertasi Penulis sebagai syarat untuk mendapat gelar Doktor bidang Ilmu Pemerintahan di Pascasarjana FISIP Universitas Padjajaran, Bandung. disamping membedah konflik Aceh dari sudut yang cukup unik, yakni penggunaan soft power, juga menampilkan data yang kaya dan matang. Sehingga menjadikan buku ini layak dikatakan “tambang emas” untuk menangani gerakan separatis di sebuah Negara.
Penggunaan kacamata yang luas serta beragam dan paling penting representatif merupakan sebuah alasan kuat reviewer mendapuk buku ini layak dibaca bagi penikmat otonomi daerah.
Substansi bahasan buku
Grand Theory yang digunakan dalam buku ini adalah Soft Power karya Joseph Nye, Jr., yang mendefinisikan soft power adalah suatu kekuatan immaterial yang lebih menekankan pada citra non-kekerasan, dibandingkan dengan hard power yang mengutamakan militerisme dan sanksi. (Hal. 3) menurut Penulis buku ini, awalnya konsep soft power ini diperkenalkan untuk menjelaskan interaksi hubungan politik antar-negara: bagaimana satu negara dengan segala kehebatannya, dapat mempengaruhi negara lain, sehingga negara lain tersebut secara ikhlas mengikuti keinginan pihak pertama.
Selanjutnya Penulis buku ini, mengkontekstualisasikan terma soft power ini untuk menjelaskan hubungan Pusat dan Daerah. Dalam hal ini adalah, bagaimana pusat mempengaruhi Aceh, sehingga Aceh mau diajak bekerjasama dalam menyelesaikan konflik.
Dalam rangka melakukan soft power sebagai upaya penyelesaian konflik maka tentu harus digunakan teori yang berkaitan dengan resolusi konflik. Karena sejatinya penggunaan soft power dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk penyelesaiaan konflik Aceh. dalam khazanah ilmu hubungan internasional, bentuk penyelesaian konflik dikenal dalam tiga bentuk, yaitu melalui negosiasi bilateral atau multilateral, mediasi oleh pihak ketiga dan keputusan hukum oleh lembaga independen (Hal. 6).
Penulis buku mengutip pendapat Miall mengenai bentuk konflik yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap cara penyelesaiannya. Miall membagi konflik dalam dua jenis, symmetric conflict dan asymmetric conflict. Konflik simetris disebabkan oleh adanya perbenturan kepentingan antara dua pihak yang memiliki entitas dan legalitas yang sama. Sedangkan konflik asimetris bersumber perebutan kepentingan antara entitas yang berbeda. Contoh seperti negara dengan kelompok pemberontak.
Jika biasanya dalam literatur yang umum dalam dunia pemerintahan, dikenal dengan desentralisasi politik, maka dalam pembahasan buku ini dipergunakan istilah politik desentralisasi. Yang berarti bahwa pemberian sebuah wewenang kepada sebuah daerah merupakan hasil dari kontestasi guna meredam konflik yang terjadi antara pemerintah Pusat dengan daerah. hal ini senada terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Cheema, Rondinelli dengan Aspinal dan Fealy, bahwa desentralisasi dimaksudkan untuk mengatasi kekeceweaan yang berkembang di daerah sehingga dengan demikian dapat mengembalikan kepercayaan rakyat di daerah dan menumbuhkan kembali komitmen mereka kepada negara kesatuan.
Secara garis besar buku ini menggambarkan penyelesaian konflik Aceh dari masa ke masa. Awalnya menggambarkan konflik Aceh dalam lintasan sejarah, dimulai dari masa awal kemerdekaan republik hingga pemerintahan Presiden SBY-JK. Didalam pembahasan ini juga digambarkan bagaimana naik turunnya hubungan pemerintah pusat dan Aceh dalam tarik menarik kepentingan dalam kewenangan kepemerintahan.
Penulis buku mencoba menggambarkan secara detail metamorfosa sebab konflik Aceh yang dimulai dari pemberontakan Daud Bereuh yang awalnya tidak sepakat dengan faham Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara. Pemberontakan Bereuh kedua disebabkan oleh digabungnya Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara sebagai konsekuensi dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda di tahun 1950. Bereuh menganggap identitas mereka patut untuk dipertahankan, maka Daud Bereuh memberontak karena tidak terakomodasinya nilai-nilai Islam yang telah lama berakar dalam pemerintahan Aceh.
Menurut Penulis Buku, Presiden Soekarno menggunakan hard power dan soft power dalam menyelesaikan konflik Aceh. Hard power ketika pemerintah menjalankan operasi militter selama periode 1953 sampai 1959. Sedangkan upaya soft power yang dilakukan Soekarno adalah dengan kembali memisahkan Aceh dari Provinsi Sumatera Utara, dengan keluarnya UU No. 24/1956. Selain itu untuk menjawab tuntutan Pemberontakan Bereuh terhadap persoalan identitas Islam, Pemerintahan Soekarno saat itu mengeluarkan Keputusan Perdana Mentri RI No. 1/Missi/1959 yang substansinya memberikan Daerah Istimewa Aceh untuk melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya dalam bidang agama, pendidikan dan peribadatan. Dengan keluarnya peraturan kedua ini, Daud Bereuh bersedia turun gunung pada Mei 1962.
Pada masa Soeharto konflik Aceh lebih disebabkan kepada ketimpangan dalam hal pengelolaan Sumber daya Alam yang dibungkus dalam nasionalisme Aceh. hal inilah yang kemudian mengilhami Hasan Tiro untuk mendirikan Gerakan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976. Perbedaan yang mencolok dari pemberontakan Daud Bereuh dengan Hasan Tiro adalah Bereuh masih menginginkan Aceh berada dalam wilayah NKRI, hanya menuntut otonomi didan pendidikan dan penerapan syariat Islam. Sedangkan Tiro menginginkan Aceh untuk benar-benar lepas dari NKRI dan mendirikan negara sendiri.
Perbedaan selanjutnya adalah Bereuh lebih pada persoalan ideologis dengan menuntut pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Sedangkan Tiro lebih cenderung pada tataran ekonomis. Masa soeharto menjadi masa air mata bagi Aceh, dimana begitu banyak korban yang melayang akibat tindakan hard power yang begitu dominan diterapkan Soeharto. Sebagaimana kita ketahui soeharto tidak akan menerima aspirasi yang berlainan dengan kehendak pusat, karenanya beragam cara dilakukan untuk membasmi gerakan separatis seperti GAM. Akibatnya para pemimpin GAM banyak berlarian ke luar negeri.
Namun begitu, penerapan hard power secara total membuat generasi pendendam di Aceh semakin marak. Hal inilah yang mengakibatkan dendam tersebut terkapitalisasi pasca kejatuhan soeharto di Mei 1998. Pada era soeharto penerapan soft power dalam penyelesaian konflik Aceh tidak ditemukan kecuali hanya sekedar mencari simpatik masyarakat. Hal ini diperlihatkan dalam operasi Bahkti TNI tahun 1990, yang “hanya” bertujuan agar masyarakat tidak bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka.
Selanjutnya resolusi konflik Aceh pada era pasca soeharto menurut penulis buku dilakukan dengan cara yang beragam. Habibie melakukan pendekatan kesejahteraan berupa pemberian amnesti kepada sejumlah tahanan politik yang terkait dengan GAM, menyalurkan bantuan dana untuk anak yatim dan janda korban konflik (hal. 39). Selanjutnya kebijakan politik desentralisasi juga dilakukan pemerintahan Habibie, dengan mengeluarkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
UU ini memberikan otonomi dan kewenangan khusus pada Aceh berkaitan pada bidang pendidikan, agama, adat dan peran ulama. Masa presiden Abdurrahman Wahid menjadi entry point bagi penyelenggaraan soft power dalam upaya resolusi konflik Aceh. pada masa gus dur inilah dimulai sebuah upaya yang menghasilkan konsesi “jeda kemanusiaan” pada 12 Mei 2000 yang difasilitasi oleh Henry Dunant Centre.
Pasca lengsernya Gus Dur dari tampuk pimpinan, pemerintahan presiden Megawati yang juga ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berhaluan nasionalis membuat tensi Pemerintah Pusat dengan GAM semakin meninggi. Ada upaya unik yang dilakukan Megawati, dikarenakan Megawati menempuh hard power sekaligus soft power dalam menangani konflik Aceh. sebelum resmi menetapkan Darurat Militer di Aceh Pada 19 Mei 2003, terlebih dahulu Megawati mengeluarkan UU No. 18/2001 yang memberikan kewenangan pada Aceh untuk memberi 70% pendapatan minyak dan gas bumi, pembentukan Wali Nanggroe, serta kewenangan Gubernur Aceh untuk menyetujui pengangkatan Kepala Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi di Nanggroe Aceh Darussalam.
Namun GAM menganngap ini sebagai upaya fait accompli bagi mereka, hingga desing senjata tidak mampu terhindarkan. Awalnya sudah ada iktikad baik dari pemerintahan Megawati untuk kembali berunding dengan GAM, namun GAM tidak juga mengurungkan niatannya untuk tidak mengajukan tuntutan merdeka. Serta tidak mau menerima otonomi yang diberikan pemerintah pusat.
Pasca pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004, menghasilkan angin segar bagi resolusi konflik di Aceh. Pemerintahan SBY-JK berkomitmen kuat untuk menyelesaikan konflik Aceh secara holistik. Hal ini diungkapkan Penulis buku bahwa sebelum maju ke meja perundingan secara resmi, Pemerintah RI mengutus farid Husein, orang kepercayaan Jusuf Kalla untuk menjalin hubungan non-formal dan kekeluargaan kepada para petinggi GAM. Follow up dari langkah ini kemudian adalah mencari sebuah lembaga yang akan memediasi perdamaian keduanya.
Berkat bantuan Juha Cristian, didapat Lembaga Crisis Management Initiative pimpinan Martii Ahtisahri yang sudah terkenal kredibel dalam menangani konflik, contohnya di Liberia, Ethiopia dan Timur Tengah. Hal baru yang dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK adalah melakukan perundingan dengan elite GAM yang tidak pernah dilakukan pemerintahan terdahulu (Hal. 86). Subtansi perundingan yang dibahas pada perundingan kali ini pun menyentuh akar persoalan, yakni pemberdayaan politik lokal dengan mendirikan partai lokal Aceh, pemberian ekonomi berupa hak bagian pendapatan dari minyak dan gas bumi sebesar 70% dan bidang sosial budaya berupa kebebasan Aceh untuk menjalankan syariat Isalm dan pelestarian adat Aceh.
Kritik terhadap Buku
Menempatkan desentralisasi secara parsial sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik merupakan jurus usang yang berulang kali diterapkan oleh pemerintah pusat. Pemberian desentralisasi yang diterapkan saat ini hanyalah merupakan respon dadakan dari pemerintah pusat atas gejolak separatisme yang melanda di negeri ini. sebagai negara yang multikultural dalam hal etnik dan budaya, sudah seharusnya pemerinah membuat blue print tentang bagaimana potensi khazanah yang ada dalam provinsi tersebut.
Solusi yang menempatkan desentralisasi sebagai “panasea” separatisme seharusnya tidak dipertahankan, karena hanya merupakan obat sementara. Namun penulis buku hendaknya menawarkan langkah solutif dan komprehensif bagi penyelesaian konflik antara Pusat dan Daerah.
Posisi penulis yang pada saat penulisan disertasi bertindak sebagai Duta Besar RI untuk Polandia membuat buku ini patut “dicurigai” tidak bebas nilai. Terlihat dari pembacaan reviewer, terlalu menyajikan secara berlebihan keberhasilan resolusi konflik yang dilakukan oleh SBY-JK. Hal ini membuat karya yang bagus ini sedikit tercemar dengan posisi penulis sebagai “bawahan” dari pemerintahan yang berkuasa. Patut juga dicurigai, karya ini bukan sebagai karya ilmiah Penulis, melainkan sekedar laporan kerja.
Penyusunan yang tercerai berai serta banyaknya pengulangan data yang ditampilkan membuat buku ini melelahkan untuk dibaca. Kadang di beberapa halaman justru malah menampilkan hal yang relatif sama dari halaman sebelumnya. Seyogyanya dalam hal menampilkan kontestasi Pusat dengan Aceh per-periode Presiden dapat disatukan dengan resolusi konflik yang dihadirkan pemerintahan tersebut, agar para pembaca tidak mendapatkan informasi yang mubazir.
Buku: Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi.
Karya: Darmansyah Djumala.
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
Oleh: Fitrah Bukhari