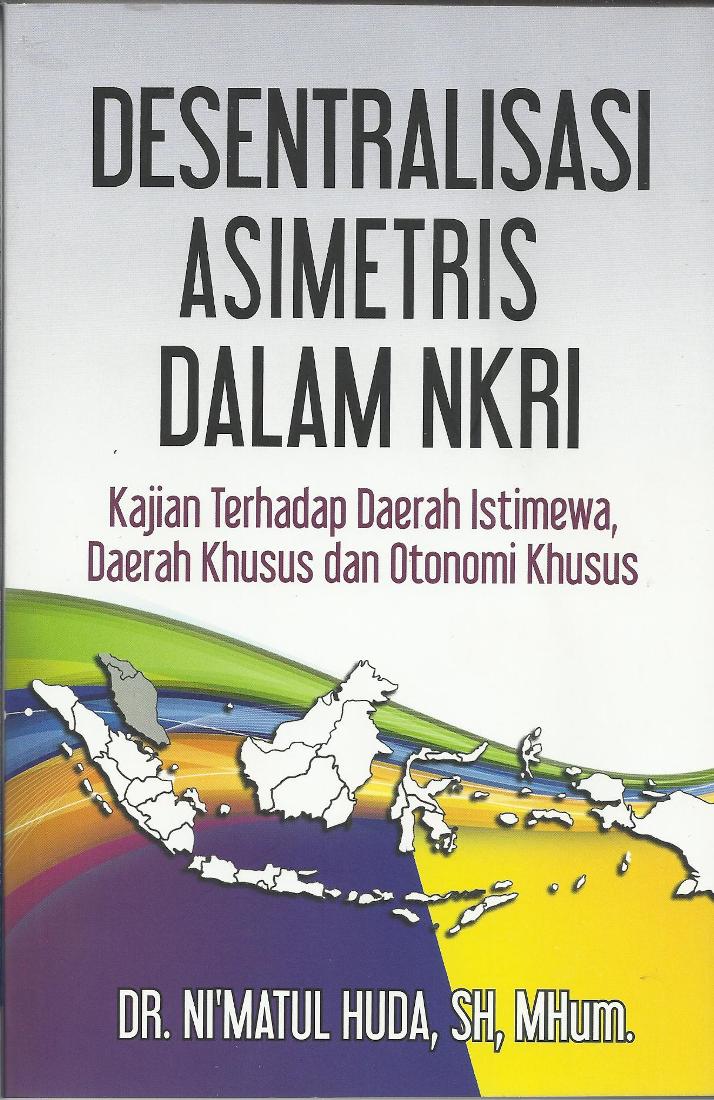Dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Karenanya Indonesia mengenal adanya keragaman terminologi status daerah, seperti daerah otonom, daerah istimewa (Yogyakarta, Surakarta, Aceh), daerah Khusus (DKI Jakarta) serta otonomi khusus (Aceh dan Papua).
Hal inilah yang menurut Charles Tarlton sebagaimana dikutip penulis buku, dikategorikan sebagai desentralisasi asimetris. Menurut Taltron, konsep ini dapat memiliki satu atau lebih unit politik maupun pemerintahan lokal yang diberikan derajat otonomi kekuasaan berupa ketidakseragaman pengaturan. Hal tersebut kemudian membentuk perbedaan derajat hubungan antar negara bagian/daerah simetris dengan unit-unit politik lainnya, baik secara horizontal (antar daerah) maupun vertikal (dengan pusat) (hal. 59).
Namun dalam prakteknya di Indonesia, pemberian kebijakan ini juga berbentuk “asimetris”, karena Negara tidak memiliki grand design soal pemberian tindakan afirmatif bagi daerah tertentu yang dipandang memiliki kekhususan. Lebih parah lagi pemberiannya hanyalah sekedar “panasea” bagi gejolak yang timbul dalam daerah.
Hal inilah yang dieksplor oleh penulis buku sehingga buku ini layak dijadikan rujukan bagi pegiat otonomi daerah, untuk melihat secara utuh dinamika regulasi penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia. Salah satu contohnya seperti Yogyakarta yang diberikan keistimewaan atas dasar historis dalam usaha mempertahankan Negara Indonesia yang baru seumur jagung.
Kita juga tidak bisa menutup mata, bahwa gejolak yang ditimbulkan sebelum pengesahan UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta turut mempengaruhi pembahasan RUU tersebut. Status jabatan Gubernur DIY yang mengalami ambiguitas dari periode per-periode menjadi penyebabnya, karenanya kelahiran UU No. 13 Tahun 2012 mampu menjadi oase bagi perkembangan Daerah istimewa Yogyakarta dalam bingkai NKRI.
Jika boleh dikatakan, satu-satunya daerah yang dimiliki desainnya oleh negara adalah DKI Jakarta. Sedari awal Presiden Soekarno berkuasa, Jakarta terus ditingkatkan statusnya dari mulai Kotapraja hingga Provinsi, bahkan Gubernur Jakarta ditempatkan setingkat Mentri. Titik tekan otonomi yang dipusatkan pada Gubernur, membuat kekuasaan Gubernur DKI Jakarta begitu kuat hingga sekarang. Sementara DKI Jakarta tidak perlu mengangkat “senjata” untuk mendapatkan perlakuan khusus, Aceh dan Papua justru mengalami hal yang paradoks.
Dalam konteks Aceh, pemberontakan Daud Bereuh hingga Hasan Tiro turut mempengaruhi dinamika sentrifugal Aceh dengan Pusat. Soekarno tahun 1951 menggabungkan Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, hingga dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
Kemudian dalam UU No. 18 Tahun 1965, Aceh diberikan hak-hak otonomi luas di bidang agama, adat, dan pendidikan. Hingga perkembangan terakhir, pasca MoU Helsinki antara GAM dengan RI, menghasilkan UU No. 11 Tahun 2006 yang didalamnya banyak hal “unik” dibanding daerah lain. Diantaranya pendirian partai politik lokal, jaminan untuk melaksanakan Syariat Islam, Wali Nanggroe, calon independen dalam Pilkada, 70% hasil semua cadangan hidrokarbon dan SDA saat ini dan masa mendatang di wilayah teritorial Aceh, serta ditempatkannya BPN sebagai perangkat Daerah.
Setali tiga uang dengan Aceh yang mendapatkan perlakuan khusus pasca “pemberontakan”, pemerintah juga menerapkan hal yang sama di Papua. Mulai dari UU No. 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Jaya Barat, pengggantian nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya, hingga gelombang reformasi melanda negeri, teriakan “Papua Merdeka” masih terdengar.
Hingga pada puncaknya 100 orang tokoh Papua bertemu dengan Presiden BJ. Habibie untuk mengutarakan aspirasi kemerdekaan tersebut. Habibie menolak dengan memekarkan Provinsi Irian Jaya, Provinsi Irian Jaya Barat, dan Provinsi Irian Jaya Tengah melalui UU No. 45 Tahun 1999. Namun pemekaran tersebut menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat, hingga akhirnya pemerintahan Megawati mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Namun hal tersebut tidak menghentikan teriakan separatis di bumi cendrawasih, karena menurut penulis buku, UU ini belum menyelesaikan akar permasalahan Papua (hal. 288).
Gelontoran dana yang banyak melalui dana otsus ternyata tidak juga mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua. Karenanya Penulis buku menyarankan agar Pemerintah dan masyarakat turut aktif mengawal pelaksanaan otsus ini, jangan sampai justru terjadi “desentralisasi korupsi” dana otsus di tanah Papua.
Namun ditengah ketiadaan grand design negara soal pemetaan potensi dan kelemahan tiap daerah, pemerintah sempat melakukan “intervensi” ke Timor-Timur. Penulis buku mengungkapkan, sejak awal proses integrasi Tim-Tim bermasalah, bahkan sampai sekarang persoalan pengungsi, tapal batas, kewarganegaraan juga masih menjadi “duri” bagi Indonesia.
Walaupun sebelum melakukan referendum Indonesia sempat menawarkan opsi otonomi khsus bagi Tim-Tim, namun ternyata upaya luhur untuk mempertahankan integrasi Tim-Tim tersebut bertepuk sebelah tangan sebagaimana hasil referendum.
Berbagai kebijakan “asimetris” Pusat dalam menjawab dinamika daerah tentu jauh dari paradigma Bhinneka Tunggal Ika, yang menuntut untuk penghargaan terhadap aspirasi masing-masing daerah. Karenanya, paradigma pembangunan daerah, seyogyanya tidak menggunakan “kacamata” Pusat an sich, melainkan harus mulai diarahkan menggunakan paradigma pemberdayaan daerah yang sesuai dengan koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yogyakarta, 30-10-2014